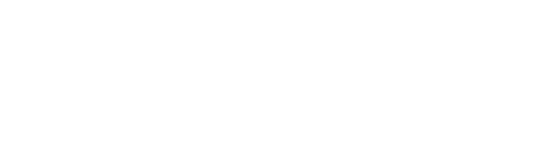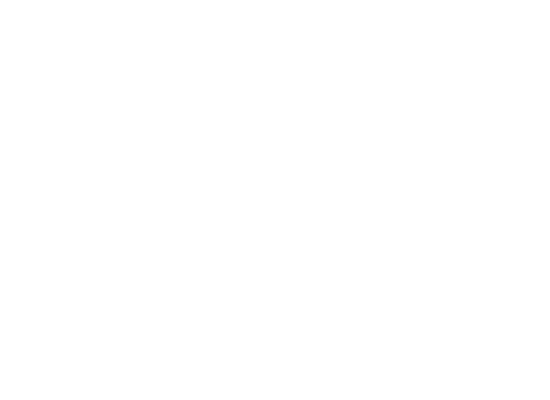Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A. (Wisuda IKJ 2005)
Pidato Ilmiah
Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A.
Pidato Ilmiah dalam Wisuda IKJ Tahun 2005
Tanggal 26 Desember 2004, gempa dan Tsunami telah memporak-porandakan Nanggroe Aceh Darussalam dengan sangat dahsyatnya, telah menghancurkan segi lahiriah fisik dan segi bathiniah mental masyarakat Aceh.
Alhamdulillah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dengan dipelopori oleh Media Group di bawah pimpinan Surya Paloh diikuti kemudian oleh berbagai perusahaan, segenap komponen masyarakat, tidak pandang agama, suku bangsa bahu-membahu bersama pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Aceh. Demikian pula langkah itu diikuti oleh dunia internasional.
Dalam membangun kembali Aceh perlu diperbesar dan diintensifkan modal sosial dan kultural masyarakat Aceh agar dapat membangun masa depan mereka lepas dari keterpurukan masa kini. Semangat hidup masyarakat Aceh harus ditumbuhkembangkan setelah musibah yang amat dahsyat itu.
Salah satu cara, bukan satu-satunya cara, dalam menumbuhkan rasa optimisme dan percaya diri, agar tidak kehilangan momentum untuk menata masa depan adalah dengan menunjukkan melalui publikasi, ceramah-ceramah, serta pelajaran di sekolah-sekolah bahwa suku bangsa Aceh telah mencapai kegemilangan dalam politik, ekonomi, agama dan budaya di masa lampau dan Insya Allah dapat pula mencapai kembali kejayaan di masa yang akan datang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelum diumumkan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam pada 12 Rabiulawal 913 H oleh Sultan Ali Mughayat Syah, telah berdiri Kerajaan Samudra Pasai Darussalam (1250-1524), yang menjadi pusat kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Dari Pasai lahir dan berkembang Bahasa Jawi yang kemudian disebut bahasa Melayu yang akhirnya melalui Sumpah Pemuda 1928 masuk ke dalam pasal 36 UUD 45 Republik Indonesia.
Islam disebarkan dari Pasai ke Patani, Melaka, dan ke Pulau Jawa. Di Pasai ditemukan puisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada nisan Sultan Pasai Malikussaleh (mangkat 1297). Seratus lima puluh tahun kemudian puisi itu dipahat pula pada nisan Sultan Melaka, Mansyur Syah dan pada nisan Sultan Pahang 35 tahun kemudian.
Pada tahun 1414 Parameswara, Raja pertama Melaka mengadakan aliansi dengan Pasai, memeluk agama Islam dan menikahi puteri Pasai. Banyak pedagang-pedagang dari Pasai pergi ke Melaka dan bersamaan dengan itu memperkenalkan sistem penempaan mata uang emas ke Melaka.
Sebagai bandar perdagangan yang telah maju pada masa itu, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Malikuzzahir yang dinamakan dirham yang kemudian sistem penempaan mata uangnya berpengaruh di Aceh serta di dunia Melayu. Melaka, Johor, Trengganu, Kelantan, Kedah, dan Brunai.
Lebih dari 220 tahun lamanya pada sisi belakang SEMUA dirham Samudra Pasai tertera ungkapan al-Sultān al-‘ādil. Setelah Kerajaan Aceh menaklukan kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1524, para sultan Aceh meniru kebiasaan para sultan Samudra Pasai dengan memakai gelar al-Sultān al-‘ādilpada dirham mereka. Hal ini terlihat pada dirham pendiri kerajaan Aceh, Sultan ‘Ali Mughayat Syah (1514-1530), sampai dirham Sultan Hussain alias Sultan ‘Ali Ri’ayat Syah (1589-1604). Di Melaka, misalnya, ungkapan al-Sultān al-‘ādil dapat dibaca pada mata uang Sultan Ahmad yang bertahta pada tahun 1510.
Dalam buku Brunei and Nusantara, History in Coinage, William L.S Barrett, pakar numismatik yang berasal dari Kanada, menulis bahwa uang emas Samudra Pasai dan Melaka yang bertuliskan Arab di kedua sisinya kemungkinan merupakan faktor dalam menciptakan mata uang timah kerajaan Brunei.
Konsep adil yang tercermin dalam numismatik dimulai di Kerajaan Islam Samudra pasai pada penutup abad ke-13 merupakan aktualisasi Firman Allah dalam Kitab Suci al-Quran. Minoritas kreatif – untuk meminjam istilah Arnold Toynbee – di kerajaan Melayu Islam Samudra Pasai telah jauh lebih awal lagi memberi makna terhadap kitab suci mereka.
Adapun bangsa Amerika Serikat baru 500 tahun kemudian, yakni ketika Perang Saudara 1860-65 melirik kepada Kitab Suci mereka, Kitab Injil. Ketika moral pasukan Pemerintah Federal AS (Union) mulai kalah melawan pasukan negara bagin Konferensi. Lahirlah motto “In God We Trust” dalam mata uang mereka. Menteri Keuangan Salmon P. Chase memerintahkan untuk membuat desain dengan inskripsi “In God We Trust” yang kemudian kembali dicetak pada tahun 1956 pada setiap uang kertas dan mata uang logam AS.
Tampak bahwa minoritas kreatif di Samudra Pasai lebih dahulu mempunyai visi jauh ke depan yang secara ideational berupaya agar umat mengurus masalah keduniawian berlandaskan iman dan taqwa mereka terhadap Allah swt. Demikianlah perihal adil itu terajut dalam jaringan intelektual kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara.
Disertasi Dr. J.J. Ras yang mendapat predikat cum laude di Rijksuniversiteit Leiden tahun 1968, membahas Hikayat Banjar yang di dalamnya diuraikan mengenai hubungan Samudra Pasai dengan Majapahit. Pangeran Pasai, Raja Bungsu, menemani kakaknya yang menjadi isteri Batara Majapahit. Ia kemudian menjadi Sunan Ampel, dan di antara keturunannya ada yang menjadi Wali Songo yaitu Sunan Bonang dan Sunan Giri.
Dalam Kitab Tazkirat at-Tabakat Qanun Syara’ Kerajaan Aceh disebutkan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan pada 12 Rabiulawal 913 H oleh Sultan Alaiddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Syah berazaskan Islam mengikut syari’at Nabi Muhammad saw dengan mengambil hukum daripada Quran dan hadist Nabi dan Qias dan Ijma’ alim ulama ahlussunnah waljamaah.
Kewajiban rakyat Aceh tertulis dalam 21 fasal, antara lain berisi kewajiban bertani lada, mengajar dan belajar pandai emas, pandai besi, pandai tembaga, beserta ukiran bunga-bungaan. Juga perempuan Aceh wajib belajar dan mengajar membikin kain sutera dan kain benang dan menjahit, menyulam, dan melukis bunga-bungaan pada kain pakaian, dsb. Diwajibkan diatas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar mengukir kayu-kayu dan mengukir batu-batu dengan tulisan dan bunga-bungaan.
Dalam kitab Tazkirat ar-Rakidin, ditulis tahun 1307 H/1889 disebutkan oleh Syaikh Muhammad Ibn Abbas, bahawa adat menurut adat hukum menurut hukm, adat dengan hukum [hukum syara’] sama kembar. Tatkala mufakat adat dengan hukum [hukum syara’] negeri senang tiada huru-hara.
Bahwa keadaan yang tersebut ini masih berlaku di Aceh dalam satu unit teritorial yang terkecil, yaitu kampung. Teungku meunasah adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan soal-soal keagamaan (hukōm) dalam suatu kampung, sedangkan geuchik adalah orang yang mewakili adat. Geuchik adalah “ayah” atau embah, sedangkan teungku meunasah adalah “ibu” kepada kampung itu. Segala sesuatu mengenai kepentingan umum di kampung ini senantiasa diurus bersama antara geuchik dengan teungku meunasah itu sebgai perlambang antara adat dengan syara’.
Pada masa Pemerintahan Ratu Tajul ‘Alam Safiatuddin Syah (1641-1675) terdapat beberapa majelis dan Balai, antara lain Majelis Mahkamah Rakyat yang anggotanya berjumlah 73 orang, yang masing-masing mewakili sebuah mukim. Dalam Qanun Meukuta Alam disebutkan nama-nama 17 orang anggota perempuan yang duduk dalam Majelis Mahkamah itu yang menunjukkan betapa tinggi sudah posisi perempuan masa itu.
 Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)
Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)
Pada tahun 1012 H atau 1603 di Istana Aceh terbit Kitab Tajussalatin atau Mahkota Segala Raja yang berisi bagaimana seharusnya perilaku serta kewajiban segala raja, menteri, hulubalang, dan rakyat dalam kehidupan bernegara menurut agama Islam. Tidaklah mengherankan bila sultan-sultan Mataram Islam merasa betapa pentingnya kitab ini dipelajari dan karenanya perlu diterjemahkan dari bahasa Melayu ke dalam Bahasa Jawa yang terjemahannya tersimpan di Kraton Solo dan Jogja dengan judul Serat Tajussalatin.
Empat orang pujangga Aceh telah berhasil mengangkat bahasa Jawi atau bahasa Melayu klasik menjadi bahasa ilmu dan kebudayaan, yang isinya membahas masalah tasawuf, ilmu agama, dan kesusasteraan. Mereka adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatra’i, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili.
Syaikh Abdurrauf menguraikan masalah-masalah ilmu hukum dalam hal ini hukum syara’ Islam dalam Kitab Mir’at al-Tullab, tertulis dalam Bahasa Jawi sebangsa bahasa Pasai atas titah Sultanah Taj al-Alam Safiatuddin Syah. Lebih dari 150 tahun sejak kitab ini dikarang, masih dipelajari oleh Raja Muda Jaafar, Raja Riau, yang ditabalkan menjadi raja pada tahun 1805, yang menurut Tuhfat an-Nafisadalah seorang raja yang salih dan kuat menuntut ilmu.
Agar pengajaran Islam menjadi lebih efektif Syaikh Abdurrauf berikhtiar menerjemahkan Kitab Suci al-Qur’an ke dalam bahasa Jawi/Melayu dan menyajikan tafsirnya berdasarkan karangan ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muhammad Syairazi al-Badawi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jawi. Inilah kitab tafsir pertama dalam bahasa Jawi/Melayu dan diberi nama Tarjuman al-Mustafid. Kitab ini pernah diterbitkan di Istambul pada tahun 1302 H [1884/1885] yang terdiri atas dua jilid. Melalui karyanya ini Syaikh Abdurrauf telah merambah jalan dan mengukir jasa dalam meningkatkan lagi kualitas iman dan taqwa umat Islam di Asia Tenggara ini terhadap Allah swt.
Pada tanggal 26 Maret 1873 dari atas Kapal Citadal van Antwerpen Belanda memaklumkan perang kepada Kerajaan Aceh. Dalam peperangan ini ditulis Hikayat-hikayat Perang Sabil yang dibacakan orang untuk memperkuat semangat jihad fi sabilillah dan Aceh adalah satu-satunya daerah yang terbanyak menghasilkan hikayat-hikayat seumpama ini. Dalam hikayat-hikayat perang yang terdapat di Aceh dinyatakan bahwa mati dalam berperang melawan Belanda yang dianggap kaphé (kafir) oleh orang-orang Aceh adalah mati syahid dan orang yang syahid akan diampunkan segala dosanya serta dimasukkan oleh Allah Ta’ala ke dalam surga. HPS juga mengajarkan bahwa perang sabil itu hukumnya adalah fardhu ’ain, yakni diwajibkan kepada semua orang muslimin, lelaki dan perempuan, tua dan muda termasuk anak-anak. Gema HPS terbukti dalam peperangan melawan Belanda. Sebagai sekedar ilustrasi kita lihat dalam pertempuran yang terjadi di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Pada pertempuran di Penosan pada tanggal 11 Mei 1904 telah gugur 95 perempuan dan anak-anak. Di Tampeng pada tanggal 18 Mei 1904 tewas 51 perempuan dan anak-anak, di Kuto Reh juga gugur 248 orang perempuan dan kanak-kanak pada tanggal 14 Juni 1904, dan di Kuto Lengat Baru tewas 316 orang perempuan dan anak-anak pada tanggal 1904.
Adapun selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, pada tanggal 15 Oktober 1945 atas nama seluruh ulama di Aceh empat orang ulama besar, yakni Tgk. Haji Hasan Krueng Kale, Tgk. M. Daud Beureu-eh, Tgk. Haji Ja’far Sidik Lamjabat, Tgk. Haji Hasballah Indrapuri dengan diketahui oleh Residen Aceh T. Nyak Arif dan disetujui oleh Ketua Komite Nasional Tuanku Mahmud, menyatakan dengan patuh berdiri di belakang maha pemimpin Ir. Soekarno yang telah memaklumkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Disebutkan juga bahwa mempertahankan Republik Indonesia adalah perjuangan suci dan diyakini sebagai Perang Sabil. Maklumat itu ditutup dengan menyerukan supaya semua patuh atas segala perintah pemimpin bangsa untuk keselamatan tanah air, agama, dan bangsa.
Ketika ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta (RI), diduduki oleh Belanda pada 19 Desember 1948 dan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta bersama beberapa pemimpin lain ditawan oleh Belanda, keadaan Pemerintah Republik sangat lemah. Tiga bulan lebih setelah ibu kota RI diduduki oleh Belanda datanglah undangan tertanggal 17 Maret 1949 dari Wali Negara Sumatera Timur, Tengku dr. Mansur, kepada Gubernur Militer Aceh, Tgk. M. Daud Beureueh, untuk menghadiri Muktamar Sumatera yang akan diadakan di Medan pada tanggal 28 Maret 1949. Yang diundang ialah Aceh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkalis, Indragiri, Jambi, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu.
Sebenarnya ada tiga pilihan bagi Aceh. Pertama, Aceh dapat meninggalkan RI dan bergabung dengan Negara Sumatera yang akan dibentuk, kedua, peluang untuk menyatakan Aceh sebagai sebuah negara merdeka, dan ketiga, tetap berada dalam pangkuan Republik Indonesia. Persepsi Aceh terhadap undangan Negara Sumatera Timur itu termuat dalam surat kabar Semangat Merdeka yang terbit di Kutaraja, ibukota daerah Aceh, tanggal 23 Maret 1949, yang memuat pernyataan Tgk. M. Daud Beureueh, Gubernur Militer, Langkat, Aceh, dan Tanah Karo, antara lain sebagai berikut.
Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republiken. Sebab itu juga, undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dari karena itulah tidak kita balas.
Selanjutnya dalam surat kabar itu Gubernur Militer yang berpangkat major jenderal tituler itu menyatakan bahwa
Kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah RI bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara per negara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.
Demikianlah semangat persatuan rakyat Aceh di bawah bendera Republik Indonesia dinyatakan oleh Tgk. Daud Beureueh. Alangkah tepatnya sikap yang telah diambil oleh Tgk. Daud Beureueh itu. Andaikata tidak demikian tentulah peta Republik Indonesia tidaklah sebagaimana yang kita warisi dewasa ini.