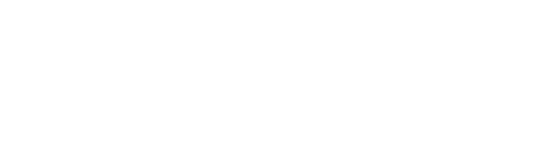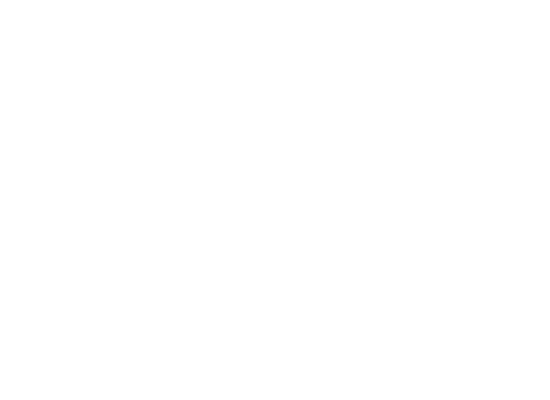Prof. Dr. M. Junus Melalatoa (Wisuda IKJ 2005)
Memahami Aceh : Perspektif Budaya
Prof. Dr. M. Junus Melalatoa
Pidato Ilmiah dalam Wisuda IKJ Tahun 2005
Indonesia dengan populasi 220 juta rakyat adalah sebuah negara-bangsa yang multikultural, sebagai hasil konfigurasi 577 kelompok etnik yang masing-masing mewujudkan variasi budayanya sendiri. Tidak ada negara-bangsa lain di dunia dengan populasi dan konfigurasi budaya yang sedemikian itu. Apakah kita, terutama pemerintah, sudah punya pemahaman secara benar perihal konfigurasi budaya itu, yang bukan hanya sekedar bisa melafalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Kalau selama ini sering terjadi sandungan-sandungan yang mencuat dari sela-sela konfigurasi itu dan sulit diatasi, itu berarti kita belum sempat mengerti tentang eksistensi konfigurasi itu.
Sebagai bagian dari Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah sebuah komunitas besar, dengan populasi empat juta jiwa adalah sebuah komunitas yang multikultural pula. Komunitas ini mewujudkan sebuah konfigurasi dari variasi budaya delapan kelompok etnik “asal” NAD, yaitu : Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulu. Masing-masing kelompok etnik ini bervariasi dalam unsur-unsur budayanya, tetapi mereka hidup berdampingan dengan sebuah persamaan, yaitu sama-sama pemeluk agama Islam. Komunitas NAD dengan populasi hanya 1,8% dari populasi Indonesia, ketika dalam tubuh NAD itu ada kasus sosial politik seperti GAM ternyata hingga memakan tempo 30 tahun kasus itu tak terselesaikan. Apakah kegagalan penyelesaian kasus seperti ini terkait dengan konfiguasi budaya yang ada, yang kita tidak sempat memahaminya sebagai bahan rujukan untuk mendapatkan solusi? Adakah dan siapa yang memahami secara benar masing-masing unsur konfigurasi dan keseluruhan konfigurasi budaya dalam komunitas NAD itu?
Pemahaman tentang sebuah kelompok etnik bisa didapat misalnya melalui sebuah karya etnografi, sebuah deskripsi holistik tentang keseluruhan unsur kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Deskripsi etnografi itu bisa juga dengan mengambil sebuah unsur yang dijadikan fokus kajian. Biasanya unsur yang menjadi fokus itu adalah unsur yang mempunyai jaringan yang luas dengan sebagian besar atau seluruh unsur-unsur kebudayaan yang lainnya. Pilihan fokus yang tepat bagi sebuah karya etnografi juga akan menghasilkan karya yang mendalam. Dengan dasar alasan tertentu, misalnya untuk karya etnografi tentang kelompok etnik Aceh, bisa mengambil unsur agama atau religi sebagai fokusnya. Agama dengan segala akidah dengan kaidah-kaidahnya atau nilai dan norma-normanya menjadi “roh” dalam unsur-unsur organisasi sosial, sistem ekonomi, teknologi, seni, bahasa, dan lain-lain. Sedangkan pada kelompok etnik lain dengan alasan teoritis atau alasan praktis bisa saja unsur budaya lain yang dijadikan sebagai fokus.
Sebuah karya etnografi yang mendalam biasanya merupakan hasil penelitian lapangan (field work) dengan metode yang tepat dari seorang antropolog. Penelitian itu biasanya dilakukan dalam tempo yang relatif lama, selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun berada di lapangan. Karya semacam ini merupakan suatu bahan dasar pemahaman tentang keseluruhan aspek kebuadayaan satu masyarakat etnik atau komunitas tertentu. Bahan pengetahuan itu dapat menjadi acuan bagi pembangunan masyarakat bersangkutan pada umumnya atau rujukan untuk mencari solusi bagi masalah-masalah khusus.
Seringkali orang berpendapat bahwa untuk penyelesaian “masalah Aceh” itu harus dilakukan dengan pendekatan kultural. Selama ini pendapat seperti ini berhenti hanya menjadi sebuah wacana tanpa tindakan atau implementasi. Mengapa? Mungkin karena bahan acuan untuk pemahaman “budaya Aceh” itu sendiri belum tersedia. Lagi pula apa yang dimaksud dengan “budaya Aceh” itu? Apakah “budaya etnik Aceh”, atau “budaya etnik Gayo”, “budaya etnik Singkil”, atau etnik yang lainnya, atau keseluruhan konfigurasi budaya dari ke delapan kelompok etnik “asal” tadi? Tidak jelas!
Sekarang kita mungkin bisa bertanya kepada pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (yang dulu) atau kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (yang sekarang) sebagai institusi garda terdepan pemegang kebijakan perihal kebudayaan. Seandainya sepakat bahwa “penyelasian masalah Aceh harus dilakukan dengan pendekatan kultural”, maka adakah dan konsepsi apa yang telah disiapkan untuk itu? Sebaliknya, beberapa tahun yang lalu kami pernah mengusulkan kepada Pemda Daerah Istimewa Aceh untuk melakukan satu penelitian lapangan guna menghasilkan etnografi tentang delapan kelompok etnik tadi, ternyata gayung tidak bersambut.
 Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)
Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)
Pertanyaannya kemudian apakah memang benar bahwa dengan pendekatan budaya itu “masalah Aceh” itu bisa selesai? Barangkali kita bisa belajar dari sejarah Aceh itu sendiri. Kolonial Belanda yang berniat menaklukkan dan menjajah Aceh harus masuk ke dalam kancah “Perang Aceh” yang memakan waktu tidak kurang dari 30 tahun yang dimulai tahun 1873. Perang yang tidak seimbang dari segi persenjataan, di mana kualitas dan kuantitas senjata pihak Belanda yang lebih baik berhadapan dengan orang Aceh yang “bersenjatakan” semangat jihat, keyakinan agama, nilai patriotisme, heroisme, dibakar oleh zikir dan lantunan hikayat Perang Sabi, Hikayat Kompeuni, dan lain-lain. Kancah peperangan ini telah menelan korban tak terbilang pada kedua belah pihak. Perang berkepanjangan ini telah membuat Belanda lelah dan prustrasi.
Dalam kemelut dan kekalutan itu Belanda rupanya harus berpikir keras untuk mencari cara lain untuk menaklukkan Aceh. Mereka harus memahami latar belakang militensi orang Aceh. Untuk itu Balanda harus memanfaatkan kemampuan seorang pakar budaya yang berkelas tak sembarangan pada zaman itu. Pakar itu tidak kurang dari Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, seorang antropolog, yang ahli tentang Islam, ahli bahasa Arab, atau bidang kebudayaan umumnya. Akhirnya untuk mendapatkan pemahaman tentang kebudayaan kelompok etnik Aceh, maka Snouck Hurgronje harus melakukan penelitian lapangan (field work) yang kemudian menghasilkan sebuah karya etnografi penting : De Atjehers, 2 Jilid (1893; 1894). Selain itu Snouck Hurgronje sempat meneliti kelompok etnik Gayo, yang kemudian juga menghasilkan sebuah karya etnografi lain: Het Gajoland en zijne Bewoners (1903).
Hasil penelitian atau karya-karya etnografi tadi menjadi bahan pemahaman tentang Aceh dan berdasarkan pemahaman itu Snouck memberikan nasehat-nasehatnya kepada pusat kekuasaan Hindia Belanda di Batavia. Para pengamat melihat Snouck sebagai seorang yang melakukan tugas intelijen dengan cara ilmiah. Berdasarkan pemahamannya tentang Aceh ia melakukan peran politik adu-domba di kalangan pemimpin Aceh waktu itu, yang tentu menguntungkan bagi Belanda sendiri.
Rakyat Aceh seperti tidak pernah reda didera masalah. Tahun 1953 meletup pergolakan “DI/TII Aceh” yang berniat memisahkan diri dari negara kesatuan RI. Pemerintah pusat berusaha meredam pergolakan ini dengan kekuatan senjata. Setelah penumpasan ini berlarut-larut, korban berjatuhan, rakyat menderita, baru timbul kesadaran bahwa “bedil” tidak selalu dapat menyelesaikan masalah semacam itu. Konflik bersenjata itu baru usai tahun 1959 setelah diberi status “istimewa”, yaitu Aceh menjadi Propinsi “Daerah Istimewa Aceh”. Isi “keistimewaan” menyangkut aspek agama, adat, dan pendidikan, yang tentunya bernuasa kultural.
Tahun 1976 pergolakan lain muncul dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selama hampir 30 tahun gerakan ini ditumpas dengan kekuatan senjata dan belum kunjung usai. Salah satu solusi yang telah diupayakan oleh negara akhir-akhir ini adalah dengan menerbitkan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu, apakah kita masih perlu berpikir untuk melakukan pendekatan kultural sebagai alternatif solusi lain? Seandainya demikian maka materi pemahaman lama dari zaman Snouck Hurgronje atau pengalaman dari zaman pergolakan “DI/TII Aceh” mungkin harus dikoreksi karena setiap kebudayaan pasti berubah. Meskipun kita amat sadar bahwa orientasi ke masa lalu masyarakat Aceh biasanya amat sangat kuat. Mereka tidak pernah melupakan kejayaan dan lebih-lebih tentang kegetiran, luka dan duka yang dialami jauh di masa silam dan pengalaman lebih akhir. Namun, menjelang masa depan yang lebih baik dan lebih damai tidak akan pernah terlambat untuk mendapatkan pemahaman tentang budaya Aceh masa kini lewat suatu penelitian, misalnya penelitian untuk menghasilkan karya-karya etnografi mutakhir.
Rakyat NAD yang lama dirundung malang, terluka, berduka, dan lelah tiba-tiba harus didera musibah dahsyat “gempa dan tsunami” yang meluluh lantakkan lingkungan alamnya, lingkungan buatan hasil peradaban Aceh, dan korban manusia yang sulit dicari bandingannya. Mereka semakin teramat lelah. Namun, konon mereka sekarang masih tetap tegar dan semakin bertaqwa sebagai gambaran akar budaya yang sebenarnya. Barangkali suasana dan kondisi seperti inilah yang patut direkan dalam karya etnografi mutakhir tentang masing-masing kelompok etnik sekaligus untuk memahami konfigurasi budaya NAD yang baru.
Sejarah telah mencatat bahwa Aceh sebagai “Daerah Modal” telah memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa Indonesia. Dengan hasil pemahaman tersebut di atas, semogalah Aceh kembali bangkit bergandeng tangan dengan warga bangsa Indonesia yang 220-an juta lainnya untuk membangun Indonesia ke depan. Dalam melangkah bersama ke depan barangkali kita patut mengenal siapa diri orang (ureueng) Aceh itu, seperti yang tersirat dalam ungkapan adat Aceh berikut ini:
Ureueng Acèh
Hana kureung hana leubèh
Meunyo até hana teupèh
Bu leubèh hana kira
Makna yang tersirat dalam ungkapan adat ini :
“Orang Aceh
Tidak kurang dan tidak lebih
Asal hatinya tidak disakiti
Ia akan memberikan segala-galanya”
Hal ini telah terbukti dalam sejarah !
Aceh telah mengorbankan jiwa raganya bersama semangat patriotisme dan heroismenya untuk mempertahankan bumi Pertiwi dari keserakahan kolonial; Aceh telah menyumbangkan pesawat Seulawah yang menjadi pesawat pertama RI pada awal kemerdekaan; Aceh telah membantu membayar gaji para pegawai di pusat pemerintahan RI ketika berada di Yogyakarta; Aceh telah menyerahkan gas alam Arun kandungan bumi Iskandar Muda; dan memberikan hasil hutannya untuk membantu meringankan beban ekonomi bangsa ini.
Lalu apa yang mereka dapat?
Sekian.