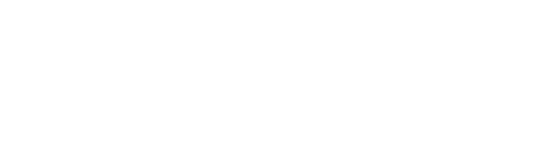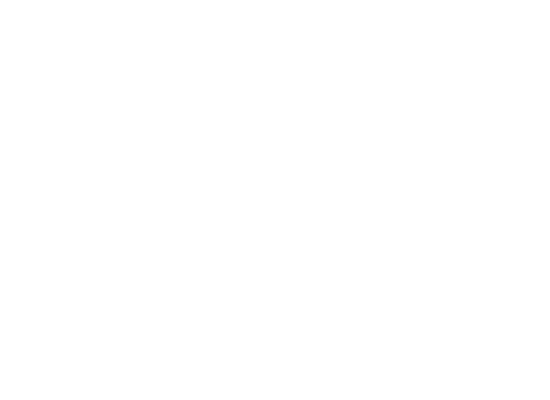Pidato Seni Dies Natalis IKJ ke-49 oleh Martin Suryajaya
Nasib Seniman di Kota Masa Depan:
Antara Keruwetan, Penghayatan dan Berkah
#1 Revolusi 4.0 sebagai Revolusi Urban
Dalam tiga tahun terakhir, ungkapan ini mestinya sudah tak asing lagi: Revolusi Industri 4.0. Istilah yang diperkenalkan oleh pendiri World Economic Forum, Klaus Schwab, pada 2015 ini memotret begitu banyak aspek khas kehidupan masyarakat urban dewasa ini dan kecenderungan-kecenderungannya. Revolusi ini adalah lompatan keempat dari serangkaian revolusi industri yang bermula sejak abad ke-18:
- Revolusi Industri 1.0 (akhir abad XVIII – awal abad XIX): mesin uap dan jaringan rel kereta api membentuk era produksi mekanis.
- Revolusi Industri 2.0 (akhir abad XIX – awal abad XX): sistem ban berjalan dan jaringan listrik membentuk era produksi massal.
- Revolusi Industri 3.0 (paruh kedua abad XX): semikonduktor dan internet membentuk era digital.
Muncul pada awal abad ke-21 dan melampaui semua revolusi sebelumnya, Revolusi Industri 4.0 adalah babak baru dalam transformasi hubungan sosial produksi yang dampaknya masih kita perkirakan saat ini. Setidaknya terdapat tiga kecenderungan besar yang menandai Revolusi Industri 4.0:
- Dominasi ekonomi platform
- Ketersambungan antar himpunan data
- Tendensi ke arah algoritma universal
Tiga hal ini membentuk kehidupan kita semua saat ini dan akan lebih menentukan lagi di masa depan. Lewat kegita hal itulah masa depan akan hadir di masa kini. Maka itu, untuk mempelajari anatomi masa depan, kita perlu membedah ketiga tendensi tersebut.
Pertama, dominasi ekonomi platform. Kita semua mengenalnya: facebook, twitter, instagram, youtube, spotify, netflix, gojek, traveloka, dll. Semua ini adalah manifestasi dari ekonomi platform yang kian dominan dalam hidup kita sehari-hari. Ada tiga corak umum dari ekonomi platform ini:
- Tendensi ke arah user-generated content: nyaris konten dari semua platform diproduksi oleh pengguna atau kreator di luar pengelola platform; yang disediakan oleh pengelola platform adalah ruang interaksi yang memungkinkan match-making antara penyedia konten dan pembutuh konten.
- Tendensi ke arah kurasi mandiri dan formasi echo chamber: dalam platform yang bercorak sosial media, semua pengguna platform bebas menilai dan mengomentari semua yang berseliweran dalam platform; tidak ada kewenangan khusus bagi kepakaran dan kurasi profesional, sehingga kurasi-kurasi mandiri itu cenderung menggumpal dalam echo chamber (atau ruang sosial yang saling meneguhkan di antara orang-orang yang sepandangan)
- Tendensi ke arah akses ketimbang kepemilikan: karena platform selalu bisa diandalkan, maka tidak ada kebutuhan untuk memiliki hal-hal dalam platform; yang diperlukan hanyalah manakala dibutuhkan, hal-hal itu selalu bisa diakses
Dominasi ekonomi platform, apabila kita cermati, adalah dominasi distributor atas produsen dan konsumen. Ekonomi platform memungkinkan produsen dan konsumen menjadi satu entitas yang sama. Produksi dan konsumsi itu fana, yang abadi adalah distribusi. Menguasai platform berarti memegang kendali atas akses. Di zaman ketika segalanya adalah persoalan aksesibilitas, mengendalikan akses berarti mengendalikan segalanya.
Kedua, ketersambungan antar himpunan data. Saat ini adalah era Big Data. Seluruh hasil interaksi pengguna dalam platform menyisakan data yang tak mungkin dikonsolidasikan oleh manusia. Namun perkembangan teknologi komputasi memungkinkan konsolidasi itu sehingga dari data besar yang terserak, kita dapat membaca pola dan tendensi. Dari sudut pandang manusia, ketersambungan antar himpunan data yang meretas batas-batas privat dan publik memungkinkan pengembangan “internet hal-ihwal” (internet of things) yang membuat kehidupan semakin nyaman. Mobil, sarana publik dan peralatan rumah tangga semakin terintegrasi dalam internet. Dari sudut pandang mesin, ketersediaan data dalam jumlah besar dan dalam frekuensi tinggi ini memungkinkan pengembangan “pembelajaran mesin” (machine learning). Dengan timbulnya kecerdasan buatan yang kreativitasnya menyerupai manusia, berbagai urusan pengambilan keputusan—di pabrik, perusahaan, bahkan lembaga politik—bisa saja dikelola oleh mesin.
Ketiga, tendensi menuju algoritma universal. Ketika arus data tanpa putus dipasok terus dari platform, semua benda-benda sehari-hari terhubung melalui platform dan mesin-mesin semakin pintar memecahkan persoalan, kita sebetulnya tengah mengantisipasi lahirnya algoritma universal. Yang dimaksud ialah semacam resep untuk membuat apa saja. Penyuntingan DNA, pencetakan tiga dimensi (3D printing), pengembangan “piranti basah” (wetware) dengan komputer berbasis karbon yang kompatibel dengan tubuh manusia, teknologi keabadian, semua itu adalah konsekuensi tak terelakkan dari Revolusi Industri 4.0. Dengan jaringan data baru yang terus tersedia secara real time, tidak dibutuhkan lompatan imajinasi yang luar biasa untuk membayangkan suatu saat di masa depan yang dekat di mana segala sesuatunya, pada prinsipnya, dapat diciptakan.
Semua energi Revolusi 4.0 ini pertama-tama akan menghantam kota-kota. Ini wajar saja, sebab segala pernak-pernik revolusi ini terlahir dari realitas kehidupan urban. Revolusi 4.0 adalah fenomena urban dan dari kota lah semuanya akan menyebarluas dan mentransformasi semua yang bukan kota menjadi kota. Hingga semua tempat, pada akhirnya, akan menjadi kota. Kota-kota apung, kota-kota bawah tanah, sebuah kota kecil di dalam kota besar.
Kita tak perlu bersusah payah membayangkan seperti apa rupa kota-kota pasca-Revolusi 4.0. World Economic Forum telah menyelenggarakan survei melibatkan 800 pimpinan perusahaan teknologi di seluruh dunia dan melahirkan prediksi keadaaan kota-kota di dunia sampai dengan tahun 2025:
- Ponsel yang ditanam ke dalam anggota tubuh tersedia secara komersial
- Sebanyak 10% manusia mengenakan pakaian yang tersambung ke internet
- Sebanyak satu trilyun sensor pada benda-benda sehari-hari akan terhubung dengan internet
- Sebanyak 50% lalu lintas internet berasal dari perkakas rumah tangga di luar sarana hiburan dan komunikasi
- Kota modern pertama dengan penduduk lebih dari 50.000 yang tidak memiliki lampu lalu lintas
- Lebih banyak transportasi dilakukan dengan berbagi sarana transportasi ketimbang memilikinya
- Mobil pertama yang diproduksi lewat pencetakan 3D
- Liver pertama yang diproduksi lewat pencetakan 3D
- Manusia pertama yang dilahirkan dengan suntingan DNA
- Manusia pertama dengan memori artifisial yang ditanam di otak
Semua itu diperkirakan, dengan kadar yang berbeda-beda, akan terjadi dalam lima tahun mendatang. Semua itu akan membentuk wajah kota-kota besar di dunia dalam tempo kurang-lebih satu pemilu lagi.
Melihat semua kemungkinan yang sangat dekat itu, orang-orang memberikan respon yang sangat beragam. Sejarawan seperti Yuval Noah Harari tenggelam dalam visi profetik tentang munculnya spesies manusia baru, Homo Deus, dan berkembangnya agama baru, agama data yang tak mengenal kematian. Wirausahawan seperti Elon Musk membangun pesawat ulang-alik untuk menghijaukan planet Mars dan membuatnya layak huni. Pemerintah Jepang mencetuskan visi Society 5.0 di mana semua kebutuhan masyarakat diladeni oleh robot. Namun saya sendiri lebih tertarik merenungkan hal lain. Ada satu hal yang mengusik hati saya: seperti apakah nasib para seniman di kota-kota masa depan?
#2 Keruwetan Hidup Seniman Urban di Masa Depan
Kalau saya bicara tentang keruwetan hidup seniman urban di masa depan, tentu kita tidak akan kaget. Seniman biasanya memang mengalami komplikasi dalam hidupnya. Namun keruwetan yang mau saya bicarakan adalah keruwetan yang khas dari masa depan—suatu keruwetan futuristik. Di masa depan, persoalan kita bukan sekadar ketidakpastian hidup dan kekurangan lapangan pekerjaan atau antitesa abadi antara seniman milyarder dan seniman paruh-waktu. Di masa depan, persoalan kita jauh lebih rumit. Mari kita periksa satu-per satu perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.
Pertama, lenyapnya kurator sebagai profesi tersendiri. Kita tahu, bahkan sekarang pun fungsi-fungsi kuratorial publik telah digantikan oleh algoritma. Ini terjadi utamanya di dunia musik dan film dengan spotify dan netflix. Berdasarkan kebiasaan kita dalam platform, mulai dari jenis musik yang sering kita dengar, jumlah musik yang kita kategorikan sebagai favorit dan rujukan silang dengan data pengguna lain yang demografinya serupa dengan kita, spotify punya fitur Discover Weekly yang menghadirkan mixtape khusus sesuai dengan selera pribadi kita (berbeda setiap pengguna) yang diperbarui tiap minggu. Konten terkurasi dengan kustomisasi personal dan frekuensi semacam itu tentunya tak mungkin dihasilkan oleh kurator-kurator kita yang paling rajin sekalipun. Dalam sastra, kurasi berbasis algoritma ini terwujud lewat pilihan buku-buku sastra di Amazon yang bukan hanya mengandalkan data pembelian kita tetapi juga data riwayat penelusuran kita di Google. Tanpa sekalipun pernah membeli buku sastra di Amazon, kita akan disodori penawaran pustaka sastra yang sesuai dengan preferensi kita manakala kita masuk ke web Amazon.
Profesi kurator seni rupa agaknya memang masih belum terjamah oleh kurasi berbasis algoritma macam itu. Persoalannya hanya waktu. Ketika nanti muncul platform digital di bidang seni rupa yang mengintegrasikan data yang sangat massif tentang karya, perupa dan para pemirsanya, niscaya fungsi kuratorial pun akan diambil alih oleh algoritma. Algoritma itu akan tahu jenis karya instalasi seperti apa yang kita sukai dan karya-karya mana saja yang perlu kita lihat kalau kita mau meningkatkan wawasan estetik kita—semua itu terjadi tanpa mengharuskan kita membaca catatan kuratorial yang berisi nama-nama angker seperti Heidegger dan Levinas. Dengan demikian, dapat kita bayangkan akan terjadi sebuah migrasi besar-besaran di masa depan: sebagian kurator akan gulung tikar atau beralih profesi, sementara sebagian lain yang konsisten di jalan kurasi akan meninggalkan kota-kota besar dan bermukim di daerah-daerah terpencil, mangkal di gapura-gapura kecamatan, dan mulai mengajarkan keindahan pada masyarakat yang belum terpapar pada algoritma.
Kedua, lenyapnya rujukan bersama dalam kritik seni. Ketika sumber-sumber pengetahuan tentang seni telah tersedia gratis dan mudah diakses, maka semua orang bisa menjadi kritikus seni bagi dirinya sendiri. Kritikus seni adalah hasil pembagian kerja pra-abad ke-21 di mana masyarakat mempercayakan pertimbangan seni pada sekelompok kecil orang yang mengabdikan hidupnya mempelajari sejarah seni dan seluk-beluk estetikanya. Dari kondisi itu, muncullah pesohor-pesohor seperti John Ruskin dan Clement Greenberg yang sabda estetiknya selalu dipercaya dan dirujuk semua orang. Kondisi ini sudah tak berlaku lagi hari ini. Literatur tentang seni maupun karya seni itu sendiri sekarang bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja. Algoritma menyediakan bacaan yang layak baca dan karya yang layak tonton untuk meningkatkan selera artistik kita.
Situasi semacam ini tidak hanya terjadi dari segi pengguna, tetapi juga dari segi kreator. Seorang musisi akan lebih percaya pada data pengguna daripada tulisan kritikus musik manakala ia hendak mencipta karya baru. Ia cukup memeriksa lagu mana yang paling sering didengar, pada menit dan detik keberapa pengguna menghentikan lagunya, serta membandingkannya dengan data pengguna musisi lain, sebagai dasar untuk memperbaiki estetikanya. Ia tak perlu mendengarkan kritikus karena kritikus tak lagi punya gigi di zaman Revolusi 4.0. Di tengah arus informasi yang sangat massif ini, orang tidak akan punya cukup rentang perhatian (span of attention) untuk mendengarkan omongan kritikus profesional. Status omongan itu akan jadi setara dengan opini seorang pemula: itu adalah satu pendapat di antara jutaan pendapat lainnya. Omongan sang kritikus profesional tidak akan ditakuti. Seandainya pun H.B. Jassin bangkit kembali di zaman digital ini, para penyair kita akan lebih takut pada omongan Netijen daripada omongan sang Kritikus. Semua orang yang pernah melihat amuk-massa di sosmed pasti sepakat.
Ketiga, lenyapnya seniman sebagai profesi tersendiri. Ketika konten audio-visual diciptakan oleh pengguna, maka seniman jadi tidak punya status khusus dibandingkan kreator konten audio-visual lainnya. Di era user-generated content ini, setiap orang adalah pencipta. Sekarang ini bukan hanya seniman yang bisa merasa terus-menerus disalah-pahami. Setiap kreator konten di sosmed pun demikian. Sekarang setiap orang bisa punya artist mentality tanpa perlu menjadi artist: merasa diri seorang jenius yang tak dimengerti, merasa lahir salah zaman, merasa karyanya hanya mungkin dimengerti oleh pemirsa di masa depan. Karena semua orang akan memproduksi karya seni, maka status seniman di masa depan hanya akan punya arti sebagai gejala pasar. Dalam konteks pasar, seniman tetap akan disegani sebagai maestro sebab ia adalah produsen benda langka (rare goods). Hanya karena produksinya dilakukan secara manual dan dalam jumlah sangat terbatas, sehingga berharga di mata kolektor, seniman masih akan dipandang. Namun dari segi orisinalitas gagasan, eksperimen artistik dan penjelajahan estetik, karya mereka akan bersaing ketat dengan karya-karya netijen.
Namun seniman bukan hanya tergusur oleh netijen. Kecerdasan buatan yang dibangun atas dasar big data dan neural network juga belakangan ini mengarah pada penciptaan karya seni. Google merilis DeepDream pada 2015 yang dapat mencipta lukisan secara mandiri dari input sembarang data visual dengan kualitas keluaran bak lukisan-lukisan Dali. Generative Adversarial Network (GAN) yang dirilis pada 2014 mampu menghasilkan lukisan potret secara otomatis dengan mutu artistik yang bersaing dengan Francis Bacon. Awal tahun ini, OpenAI merilis MuseNet yang dapat menggubah komposisi musik sepanjang 4 menit dengan 10 instrumen berbeda. Pada tahun 2016, Ars Technica berhasil mengembangkan AI yang dapat menulis skenario film pendek berjudul Sunspring berdasarkan input dari 100 skenario film sci-fi. Dua tahun kemudian, AI yang menamai dirinya sendiri sebagai Benjamin itu menciptakan film pendek dengan stok gambar dari film-film public domain. Hasilnya adalah Zone Out, sebuah film sepanjang 5 menit dengan wajah-wajah, voice acting, skenario, pengadeganan, montase dan scoring yang semuanya dikarang sendiri oleh Benjamin.
Keempat, lenyapnya museum dan galeri seni sebagai ruang pamer. Ketika platform digital dengan teknologi VR semakin memungkinkan simulasi ruang pamer, maka pameran masa depan akan lebih banyak dilakukan di ruang-ruang virtual. Perkembangan teknologi VR saat ini telah mengarah bukan saja reproduksi citra visual tetapi juga reproduksi sensasi taktual. Di dunia video games, misalnya, berkembang teknologi Oculus Rift yang mengenali sensor gerak tubuh dan menjadikannya input dalam interaksi virtual. Umpan balik yang diberikan pada pengguna saat ini masih pada tahap getaran. Namun bukan tak mungkin dalam tempo yang tak terlalu lama umpan balik itu akan menjadi lebih akurat, semakin menyerupai sensasi menyentuh permukaan benda. Dengan demikian, museum dan galeri seni sebagai ruang pamer akan tergantikan fungsinya dengan simulasi digital yang akurat. Kita bisa membayangkan dalam satu dekade ke depan, kita menghadiri pameran Documenta tanpa perlu pergi ke Kassel. Ketika itu terjadi, fungsi museum dan galeri seni akan bertransformasi menjadi gudang dan kantor dengan server yang dipelihara dengan penuh perhatian selayaknya benda-benda koleksi.
Inilah realitas masa depan. Realitas kehidupan urban ke depan akan lebih eksperimental daripada kesenian yang paling eksperimental, lebih politis dari kesenian yang paling politis, lebih ngaco dari kesenian yang paling ngaco. Mau seni partisipatoris? Cukup donlot tik-tok atau smule. Mau estetika relasional? Cukup donlot tinder atau okcupid. Mau jadi seniman jenius yang selalu disalah-pahami? Cukup debat di facebook lawan netijen. Seniman performans belajar menulis catatan kaki sampai S3, sementara Pak Eko mempraktikkan seni performans di tengah-tengah kesibukannya sebagai pulisi. Seniman media baru memproduksi belasan editan photoshop dengan mutu artistik tinggi, sementara produsen hoax SARA memenuhi dunia maya dengan ribuan foto yang diedit seperlunya dengan Paint. Yang satu membuat orang tertawa di depan sosmed, yang lain menggerakkan orang untuk turun ke jalan dan melempar bom molotov. Seniman partisipatoris tinggal bersama warga untuk membangun narasi baru tentang masyarakat yang lebih adil lewat praktik seni seturut ideal-ideal Augusto Boal, sementara provokator sosmed terjun ke grup-grup facebook dan WA membangun narasi baru tentang bumi datar, tentang Gaj Ahmada, tentang vaksinasi yang mengandung babi. Yang satu menghasilkan LSM, yang lain menghasilkan amuk-massa.
Inilah keruwetan-keruwetan hidup seniman masa depan yang tak terbayangkan bahkan oleh Marinetti sang dedengkot futurisme satu abad yang lalu. Dan keruwetan ini tak hanya melanda hidup kreatif sang seniman, tetapi juga hidupnya sebagai manusia. Kita tidak membutuhkan imajinasi super untuk membayangkan adanya, di masa depan, sebuah teknologi VR yang menstimulasi sensasi keindahan pada otak dalam bentuk-bentuk yang spesifik dan bahkan taktual: sensasi meraba tekstur lukisan Affandi,.sensasi menonton Tiga Dara di bioskop Capitol era 1950-an, bahkan sensasi menjadi seniman beken di era Boom seni lukis Indonesia. Toh semua sensasi kita merupakan efek elektro-kimiawi dalam otak yang selalu dapat distimulasi apabila kita tahu pada titik mana saja stimulasi itu harusnya diberikan. Lapangan kerja seniman untuk menghadirkan keindahan melalui artifak pada pemirsa akan digusur oleh para neurosaintis yang piawai menstimulasi sensasi keindahan secara langsung (tanpa melalui artifak konkrit). Untuk apa belajar susah-susah soal montase dialektis atau time-image apabila teknologi telah memungkinkan kita mengalami langsung bagaimana rasanya dielu-elukan selepas memberikan pidato kemenangan di Cannes atau Berlinale dengan hanya memakai helm VR?
Dalam situasi seperti itu, dari mana seniman urban kita memperoleh penghidupannya? Bagaimana mengelola ketidakmenentuan dan kerawanan hidup seniman urban di era 4.0? Ini merupakan sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Barangkali lain soalnya dengan seniman-seniman daerah yang hidup di kabupaten. Mereka masih bisa mengusahakan praktik seni tradisi dan bertopang pada jejaring tolong-menolong komunal yang ruwet tapi bisa diandalkan. Hal semacam itu masih bisa terjadi di Jakarta pada era 1950-an, seperti pada cerpen-cerpen Keajaiban di Pasar Senen karya Misbach Yusa Biran. Namun Jakarta di masa itu adalah seperti kampung yang besar, sulit dibandingkan dengan Jakarta metropolitan masa kini apalagi Jakarta 4.0 belasan tahun yang akan datang. Itulah sebabnya, perkaranya lain bagi seniman urban kontemporer kita.
#3 Para Penghayat Kesenian di Masa Depan
Dihadapkan pada semua fakta ini, sebagian dari kita mungkin akan berusaha memobilisasi argumen-argumen jiwa kethok. Dengan mengenang Bapak Seni Rupa Modern kita, kita bisa saja berpendapat bahwa ada sesuatu yang tak mungkin dihasilkan oleh algoritma dan praktik artistik aksidental dari netijen. Bahwa sesuatu itu adalah rasa seni. Bahwa ada semacam sensasi keindahan yang membungahkan hati. Bahwa ada semacam ruh dan kegaiban lainnya yang merasuki seniman ketika berkarya atau pemirsa yang tengah mengamati hasil karya.
Dengan demikian maka dimulailah kisah para penghayat kesenian di masa depan. Seperti para penghayat kebatinan saat ini yang tergerus oleh dominasi agama mainstream, para penghayat kesenian di masa depan itu akan memiliki ritual-ritualnya sendiri. Mereka akan terus menggelar diskusi-diskusi tentang pemberontakan estetik, sementara di dunia maya pemberontakan estetik terjadi setiap detik. Mereka akan terus mengusahakan pameran-pameran seni yang dikurasi oleh kurator profesional, sementara di luar sana bilangan 1 dan 0 mengkurasi musik sambil membuka email dan mengajarkan seorang mahasiswa, di belahan dunia lainnya, bagaimana caranya menjadi pensiunan tanpa harus bekerja. Mereka akan terus menjalankan ritual-ritual street art, selalu merasa diawasi, selalu merasa harus klandestin, di zaman ketika represi dan dominasi terjadi sesederhana mencontreng EULA dan Terms of Service.
Seniman media baru, seniman media lama, seniman media alternatif, seniman lintas-media, seniman tanpa media—semuanya akan tergerus dan terpojok seperti binatang yang terluka. Dalam usaha penghabisan untuk menyelamatkan marwah kesenian, mereka semua akan membentuk sebuah perkumpulan seni terakhir, suatu kelompok penghayat kebatinan seni Indonesia, lalu mereka akan berdebat tentang prinsip-prinsip estetika, tentang akses ke jaringan kolektor, tentang akses ke pendanaan pemerintah, lalu akan terjadi split, fragmentasi, lalu semuanya akan berlomba-lomba menulis otobiografi.
Saya bayangkan suatu hari di masa depan, saya akan datang ke museum seni kontemporer dan mendapati aki-aki seni rupa Indonesia bertopi fedora dengan syal di leher duduk-duduk di atas ambin reyot seperti orang tidak ada kerja. Dan salah seorang dari mereka akan bercerita tentang masa keemasan seni rupa Indonesia—dengan satu tangannya menunjuk ke arah matahari sementara tangan satunya lagi dengan hati-hati menahan tatakan cangkir berisi sececap kopi. Saya bayangkan seniman-seniman rebel sewaktu muda yang menua sebagai pemburu dana fasilitasi kesenian dari pemerintah. Saya bayangkan pengemudi gojek pendiam yang sewaktu muda pernah memenangi Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Saya bayangkan gelandangan-gelandangan futuristik luntang-lantung di Cikini Raya dengan wawasan estetika yang kaya. Saya melihat TIM di masa depan, saya melihat XXI di masa depan, saya melihat masa lalu di masa depan. Saya melihat dan mengerti: segala sesuatunya akan jadi Balai Budaya.
Tentu, saya tidak bisa membayangkan semua hal. Ada banyak hal yang tak bisa saya bayangkan. Saya tak bisa membayangkan nasib para seniman partisipatoris di masa depan, seperti halnya saya tak bisa membayangkan nasib LSM-LSM di masa depan. Saya tak bisa membayangkan nasib galeri-galeri seni di masa depan, seperti halnya saya tak bisa membayangkan galeri-galeri ATM di mall-mall masa depan. Saya tak bisa membayangkan kritikus seni di masa depan, seperti halnya saya tak bisa membayangkan kritikus seni di masa kini. Saya pun tak berani membayangkan apa nasib sastrawan—yang paling menyedihkan di antara semua seniman—di kota masa depan.
Lalu di mana sebetulnya, kita bertanya, letak kesenian pada bentang kenyataan masa depan? Jawabnya, tentu saja, adalah di lubuk hati orang yang percaya. Hanya di sanubari para penghayat kesenian lah masih ada seni di masa depan, bertentangan dengan semua fakta empiris bahwa seni telah luruh ke dalam jagad besar manusia urban dan lenyap untuk selama-lamanya. Nasib seni kontemporer di masa depan akan sama seperti apa yang biasa kita sebut, dalam penghormatan yang khusyuk kepada para pinisepuh, “seni tradisi”. Seni kontemporer kita akan tinggal di ruang gelap di mana hanya ada nyala pelita (yang melambangkan ketakutan) dan kertak gigi (yang melambangkan keberanian). Seperti para empu keris zaman kuno, para perupa kita akan menjadi pengrajin benda-benda langka yang sarat narasi ajaib, semacam inspirasi gaib yang ditarik keluar dari sudut-sudut wingit sejarah seni rupa Indonesia. Seperti para penatah relief anonim dari wangsa Syailendra, para street artist kita akan menjadi bagian dari street itu sendiri. Dan seperti terhadap berbagai bentuk seni tradisi saat ini, pemerintah kota masa depan akan mulai mencanangkan program pelestarian seni kontemporer: membudayakan kembali seni instalasi dalam rangka menunjang sinergitas antar pemangku kepentingan, lomba kritik film indie di panti jompo dalam rangka peringatan hari Kesaktian Pancasila, peresmian kawasan wisata seni media baru di jalan Surabaya.
Semuanya akan menjadi tradisionil pada waktunya. Semuanya akan menjadi tradisionil pada waktunya. Yang avant-garde, yang eksperimental, yang posmo, yang anti kemapanan, yang Deleuzian, yang delusional, yang pernah menantang dunia, yang pernah berjuang dan berhasil, yang pernah berjuang dan gagal, yang pernah mengkhianati seni tapi membalasnya seribu kali, yang modernis, yang high modernist. Semuanya akan menjadi tradisionil pada waktunya.
#4 Berkah Dunia Ketiga
Semua yang saya sampaikan, tentu saja, berlebih-lebihan. Tak ada yang tahu pasti apakah prediksi-prediksi World Economic Forum itu akan terjadi dalam lima tahun lagi. Tak ada yang tahu pasti apakah imajinasi-imajinasi saya akan jadi kenyataan dalam lima dekade mendatang. Yang jelas kita ketahui saat ini adalah bahwa akan terjadi perubahan-perubahan signifikan dalam waktu-waktu mendatang akibat Revolusi Industri 4.0. Kesenian tidak akan luput tanpa dampak secuil pun dari gelombang transformasi ini. Dan kesenian di kota akan terkena dampak paling awal. Apa yang saya ungkapkan hanyalah tantangan untuk memikirkan kembali praktik kesenian yang kita jalani saat ini: apakah kesenian masih mungkin di era revolusi 4.0, apakah sebetulnya yang esensial dari praktik berkesenian dan apa yang cuma embel-embel, sejauh mana kesenian urban kita merespon politik hidup bersama.
Lagipula, kita juga punya alasan untuk bersyukur. Hal-hal baru biasanya agak lelet tiba di dunia ketiga. Sehingga kita punya waktu untuk mengatur siasat. Dan kalaupun tiba, kita selalu bisa mengandalkan deformasi alamiah yang muncul dari praktik-praktik khalayak ramai. Selalu ada glitch ketika kecanggihan-kecanggihan dunia pertama sampai pada dunia ketiga. Seperti pada video penuh noise yang muncul akibat codex yang tidak kompatibel, Revolusi 4.0 pun akan kita serap dengan penuh glitch. Untuk itu, kita mesti bersyukur. Dari situlah hal-hal baru muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal-hal yang secara estetis mengagetkan tanpa perlu dipajang dan diterima dalam medan sosial seni.
Untuk melihat glitch itu, kita hanya perlu mengambil satu langkah mundur untuk melihat kenyataan sebagai sebuah keseluruhan. Kita dapat mengatakan bahwa keseluruhan konstruksi hidup urban kita di dunia ketiga adalah karya seni. Kemacetan-kemacetan yang tak terselesaikan, trotoar yang dialihfungsikan jadi pasar, banjir musiman yang selalu mengagetkan—seluruh kekacauan hidup bersama inilah karya seni kita. Kota adalah karya seni kita. Kita membuatnya bersama-sama dan kita menikmatinya bersama-sama. Kecanggihan teknologi dari dunia pertama tidak dapat melunturkan kecupetan pikiran kita yang tersekat-sekat dalam prasangka etno-kultural. Komersialisasi hidup urban yang kaya oleh unggun-timbun komoditas tidak dapat mengendorkan obsesi kita pada kesalehan. Dari situlah muncul ide-ide kreatif untuk membuat aplikasi yang dapat memantau kelompok aliran kepercayaan dilengkapi dengan fitur untuk melaporkannya ke polisi atas dasar ajaran sesat. Dari situlah muncul inspirasi untuk memurnikan diri dengan menjorok-jorokkan orang lain. Dari silang-sengkarut itulah lahir karya seni kita: kota Jakarta.
Di sini kita jumpai suatu kemungkinan jalan keluar dari tantangan Revolusi Industri 4.0. Ada suatu hal yang tak bisa ditiru oleh mesin berkecerdasan. Mesin-mesin berkecerdasan didesain untuk cerdas seperti manusia; mereka diajari cara berpikir yang konsisten, sistematis, runut, dan masuk akal. Padahal tantangan tersulitnya adalah menjadi bodoh seperti manusia. Inkonsistensi kita lah—bicara toleransi tapi berbuat intoleran, mengkhayalkan hidup saleh tapi gemar belanja, menjadi mayoritas tapi merasa terancam seperti minoritas—inkonsistensi kita itulah yang sulit ditiru oleh mesin-mesin berkecerdasan paling canggih saat ini. Begitu berhadapan dengan inkonsistensi, mesin-mesin itu akan mengalami crash, galat fatal yang membuat sistemnya mesti dihidupkan kembali. Lain halnya dengan manusia yang terbiasa hidup dengan inkonsistensi, bahkan menganut pandangan-pandangan yang inkonsisten satu sama lain, seperti percaya pada kaidah sains modern sekaligus hoax SARA yang paling dangkal.
Bukan kecerdasan kita yang sulit ditiru, melainkan kebodohan kita. Sebab kecerdasan kita terbatas, sedangkan kebodohan kita tidak terbatas. Dalam irasionalitas tak terhingga itulah kita dapat menghasilkan karya seni yang tak mungkin ditiru oleh mesin-mesin berkecerdasan. Irasionalitas kita adalah sumber inspirasi yang tak ada habisnya. Dengan menimba sumur inspirasi itu, kita mencipta berbagai karya kreatif—berbagai aplikasi dan konten audio-visual—yang menjunjung tinggi toleransi pada kaum mayoritas, meningkatkan konsumsi kabar burung, dan secara kreatif mengemas banjir sebagai berkah. Di situlah juga kita menaruh harapan pada suatu jenis kesenian yang tak mungkin direnggut oleh Revolusi Industri 4.0, yakni kesenian yang adalah kekacauan yang adalah kehancur-leburan segala sesuatu.***