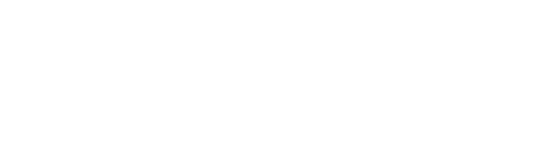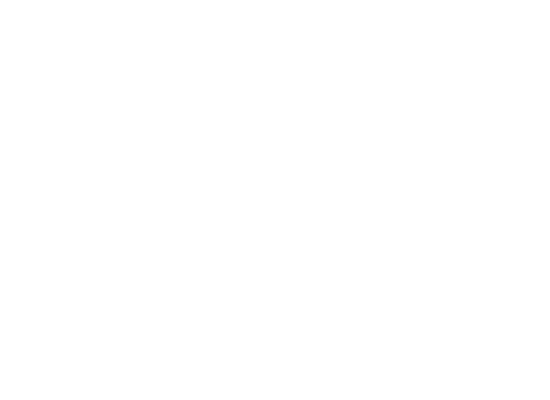Hilmar Farid, Ph.D. (Wisuda IKJ 2014)
SENI DENGAN TUJUAN
Hilmar Farid, Ph.D.
Pidato Ilmiah dalam Wisuda Institut Kesenian Jakarta Tahun 2014

Izinkan saya membuka pidato ini dengan cerita tentang sebuah foto yang dibuat oleh Kevin Carter, seorang fotografer asal Afrika Selatan, pada awal tahun 1993 di Sudan bagian selatan. Foto itu menggambarkan seorang anak kecil berkulit hitam dan kurus yang duduk meringkuk di tanah. Tubuhnya condong ke depan seolah ingin bergerak maju tapi tidak punya cukup kekuatan. Di belakangnya ada seekor burung bangkai yang seolah sedang menunggu anak itu menemui ajalnya. Foto itu diterbitkan pertama kali di harian New York Times pada 26 Maret 1993 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Reaksi publik terhadap penerbitan foto ini sangat menarik. Redaksi New York Times mendapat serbuan telepon dan surat yang menanyakan nasib anak itu. Tidak sedikit yang mengecam Kevin Carter karena tidak segera menyelamatkan anak itu dari ancaman burung bangkai tapi malah memotretnya.
Kontroversi semakin meluas ketika cerita di belakang foto itu mulai beredar. Carter sendiri mengaku menunggu sekitar 20 menit sebelum memotret dengan harapan agar burung bangkai itu mengepakkan sayap agar efek visualnya lebih dramatis. João Silva, seorang fotografer Portugis, yang juga ada di lokasi bersama Carter saat itu, bercerita bahwa Carter mengambil foto itu ketika para petugas operasi kemanusiaan PBB sedang membagikan makanan kepada penduduk. Semua penduduk dewasa antre di tempat pembagian makanan meninggalkan anak-anak mereka di belakang. Ia juga menjelaskan bahwa Carter sengaja memilih sudut yang tepat agar burung bangkai itu terlihat lebih dekat daripada sesungguhnya. Setahun setelah foto itu beredar Carter memperoleh Hadiah Pulitzer untuk feature photography.
Penghargaan tersebut justru membuat kontroversi di sekitar foto itu semakin ramai. Sebagian kritikus menilai bahwa Carter adalah burung bangkai yang sesungguhnya karena menggunakan penderitaan anak kecil itu untuk kepentingan karirnya sendiri. Ada juga yang mempersoalkan framing dari foto itu yang tidak menghadirkan realitas apa adanya tapi sengaja bermaksud mengundang kemarahan publik terhadap keadaan di Sudan. Foto itu sendiri memberi kesan bahwa anak kecil itu sendirian menghadapi ancaman alam dalam bentuk burung bangkai. Tidak ada tanda adanya pemukiman, perlindungan, atau adanya orang dewasa yang bisa membantu anak itu. Padahal dari cerita Carter dan Silva kemudian kita tahu bahwa kenyataannya tidaklah begitu. Bagi sebagian kritikus framing seperti itu adalah bentuk manipulasi sentimen publik.
Di satu sisi tujuan itu baik adanya. Saat foto itu dibuat Sudan sudah dilanda konflik bersenjata selama sepuluh tahun. Kelaparan dan penderitaan bukan baru sehari terjadi. Tapi publik membiarkan karena menganggap apa yang terjadi di sana adalah masalah dalam negeri Sudan. Foto itu mengubah persepsi publik bahwa yang terjadi di Sudan bukan sekadar konflik bersenjata tapi sudah berubah menjadi bencana kemanusiaan yang memerlukan uluran tangan dari luar. Di sisi lain kritikus juga menilai bahwa foto tersebut membuat Sudan terlihat tidak berdaya dan hanya bisa diselamatkan oleh pihak lain. Padahal sumber masalah yang membuat Sudan tidak berdaya justru adalah warisan campur tangan pihak lain dalam bentuk kolonialisme selama hampir dua abad. Kita tahu kemudian bahwa perhatian publik dunia dalam bentuk operasi kemanusiaan di Afrika akhirnya menimbulkan ketergantungan yang akut dan sederet masalah lain.
Diskusi dan kontroversi di sekitar foto itu menunjukkan kekuatan seni dalam kehidupan sosial kita. Karya seni di sini tidak sekadar menghadirkan realitas apa adanya tapi secara aktif menghadirkan sebuah narasiyang membentuk persepsi mengenai realitas atau dengan kata lain turut membentuk realitas itu sendiri. Persepsi kita mengenai realitas itulah yang kemudian membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu dan mengubah realitas yang kita lihat. Dalam kasus foto yang dibahas di atas, fotografer itu menghadirkan sebuah narasi tentang apa yang terjadi di Sudan. Narasi itu kemudian membentuk persepsi publik bahwa masyarakat di sana, yang diwakili oleh anak kecil itu, memerlukan pertolongan. Dan persepsi publik itulah yang mendorong para pemimpin politik untuk melakukan intervensi baik dengan cara meningkatkan operasi kemanusiaan maupun dengan mengupayakan perdamaian.
 Karya seni dalam konteks ini jauh lebih besar kekuatannya daripada setumpuk laporan mengenai keadaan di Sudan yang diproduksi oleh lembaga pemerintahan, lembaga kemanusiaan internasional maupun organisasi hak asasi manusia selama sepuluh tahun berlangsungnya konflik bersenjata di sana. Dalam kebudayaan yang sangat visual sekarang ini kekuatan tersebut sepertinya semakin berlipat-ganda dan menjadi mengerikan jika tidak dikelola dengan baik. Sebuah tema lama dalam dunia seni, yakni tanggung jawab sosial dari seniman, menjadi relevan dibicarakan lagi di sini. Tapi fokusnya bukan pada dimensi etis dari sebuah karya saja melainkan lebih luas mengenai kedudukan seniman dalam masyarakat dan tanggung jawabnya sebagai pemilik dan pengendali kekuatan yang begitu besar terhadap masyarakat tersebut.
Karya seni dalam konteks ini jauh lebih besar kekuatannya daripada setumpuk laporan mengenai keadaan di Sudan yang diproduksi oleh lembaga pemerintahan, lembaga kemanusiaan internasional maupun organisasi hak asasi manusia selama sepuluh tahun berlangsungnya konflik bersenjata di sana. Dalam kebudayaan yang sangat visual sekarang ini kekuatan tersebut sepertinya semakin berlipat-ganda dan menjadi mengerikan jika tidak dikelola dengan baik. Sebuah tema lama dalam dunia seni, yakni tanggung jawab sosial dari seniman, menjadi relevan dibicarakan lagi di sini. Tapi fokusnya bukan pada dimensi etis dari sebuah karya saja melainkan lebih luas mengenai kedudukan seniman dalam masyarakat dan tanggung jawabnya sebagai pemilik dan pengendali kekuatan yang begitu besar terhadap masyarakat tersebut.
Untuk membahas masalah ini saya kira pembedaan antara profession dan vocation yang dibuat oleh ahli sosiologi Max Weber menjadi penting. Dalam bahasa Indonesia terjemahan yang paling tepat dari profession adalah pekerjaan dalam pengertian yang biasa kita gunakan sehari-hari, sementara vocationpaling tepat diterjemahkan sebagai panggilan atau pengabdian. Dalam masyarakat kita, memiliki pekerjaan dan bersikap profesional dalam pekerjaan itu dinilai sebagai keberhasilan. Di satu sisi hal itu benar, tapi di sisi lain ada masalah yang timbul jika pekerjaan dan profesionalisme menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kembali kepada contoh Kevin Carter di atas: Carter punya pekerjaan sebagai fotografer dan menjalankan tugasnya sebagai seorang profesional. Profesinya menuntut dirinya untuk mendapatkan gambar terbaik mengenai keadaan di sana dan bukan untuk menolong anak yang tengah terancam keselamatannya.
Profesi dan panggilan atau pengabdian adalah dua hal yang bisa sangat erat kaitannya tapi bisa juga sangat bertolak belakang. Profesi terarah pada hasrat untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual untuk menyambung hidup sementara pengabdian terarah pada keinginan untuk berbuat sesuatu yang belum tentu menguntungkan dari segi material maupun spiritual. Profesi didorong oleh aspirasi sementara pengabdian didorong oleh visi. Seorang profesional akan melakukan segala pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik dan terukur tanpa banyak bertanya, sementara seorang pengabdi atau orang yang memenuhi panggilan akan terlebih dulu berpikir apakah pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan nilai yang dipegangnya? Profesi dalam pengertian itu berpusat pada diri sendiri – apa gunanya bagi saya, apa urusannya dengan saya, dan seterusnya – sementara pengabdian atau panggilan mempertimbangkan arti segala sesuatu bagi orang lain juga.
Seni pada awalnya adalah bentuk pengabdian yang dilakukan bersamaan dengan ritual atau bahkan menjadi ritual itu sendiri. Baru dengan datangnya modernitas maka seni terpisah sebagai sebuah bidangyang berdiri sendiri terpisah dari dunia ritual dan pengabdian yang menjadi asalnya. Bersamaan dengan itu pula kedudukan orang yang memiliki kemampuan artistik mulai berkurang arti pentingnya dalam masyarakat. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya posisi itu semakin merosot. Sebagai contoh sekarang ini sedikit anak yang jika ditanya “mau jadi apa kalau sudah besar?” akan menjawab “jadi seniman.” Di masa sekarang kerja kantoran yang kadang tidak masuk akal itu dianggap jauh lebih nyata dan konkret daripada menjadi seniman. Tidak heran jika banyak seniman yang kemudian bergulat agar apa yang dilakukannya diakui sebagai profesi yang sah (jika tidak di mata publik, setidaknya di mata mertua).
Begitu besar keinginan untuk menjadi profesional sampai segi vocational dari seni jadi diabaikan. Lagi kasus Carter menarik sebagai contoh di sini. Apakah dengan mengabaikan keselamatan anak itu dan menunggu 20 menit untuk memotret Carter bersikap profesional? Jawabnya adalah ya. Dan karena itulah bersikap profesional saja tidak cukup dalam kehidupan, apalagi bagi seorang yang bekerja di bidang seni dengan pengaruh dan kekuatan yang begitu besar. Tentu ini bukan isu yang mudah karena di sisi lain seandainya ia memenuhi panggilan sebagai warga dunia dengan rasa kemanusiaan dan menyelamatkan anak itu dari gangguan burung maka foto itu tidak akan pernah dibuat dan dunia mungkin tidak akan pernah tergerak untuk membantu Sudan. Karena itulah diskusi tentang perbedaan profesi dan pengabdian tidak pernah bersifat hitam-putih tapi senantiasa akan berjalan di garis batas (liminal).
Kenapa kita perlu diskusi semacam itu sekarang? Tidak lain karena ketegangan antara profesi dan sikap profesional di satu pihak dan pengabdian atau panggilan di pihak lain akan semakin mengemuka. Ada banyak masalah yang timbul dalam kehidupan kita justru karena pengutamaan profesi dan sikap profesional. Bekerja secara ‘profesional’, artinya mampu menyelesaikan pesanan sesuai target dan waktu, dianggap sebagai sebuah kualitas yang baik pada dirinya, terlepas dari apakah yang dikerjakan adalah sesuatu yang buruk bagi masyarakat. Orang seperti ini akan menduduki tempat lebih terhormat di mata publik daripada orang yang sepanjang karirnya mengabdi untuk memerangi ketidakadilan. Kekacauan neraca ini yang saya kira membuat kita harus kembali mendiskusikan semua masalah ini secara serius. Bukan untuk secara absolut menentukan mana yang lebih baik tapi untuk menyadari bahwa tiap pilihan yang diambil pada akhirnya punya konsekuensi luas dan terkait dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Membiarkan seni dan kerja kreatif menjadi profession atau pekerjaan semata-mata berarti mereduksi seni dan kerja kreatif ke urusan bentuk dan ketrampilan membuat bentuk yang bisa dipakai untuk kepentingan atau isi apapun juga. Artinya seni tidak lagi punya tujuan dan kendali atas kekuatan besar untuk mempengaruhi publik dan mengubah realitas yang inheren dalam karya seni sepenuhnya berada di tangan pihak lain. Kita perlu kembali melihat seni sebagai vocation atau pengabdian terhadap nilai yang lebih besar daripada kepentingan orang per orang. Kesadaran bahwa seni punya kekuatan besar untuk mempengaruhi publik dan turut membentuk realitas adalah dasar bagi kita untuk memikirkan kedudukan seniman di dalam masyarakat dan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat tersebut. Saatnya kembali berkesenian dengan nilai, prinsip dan tujuan.