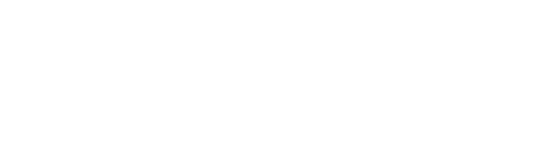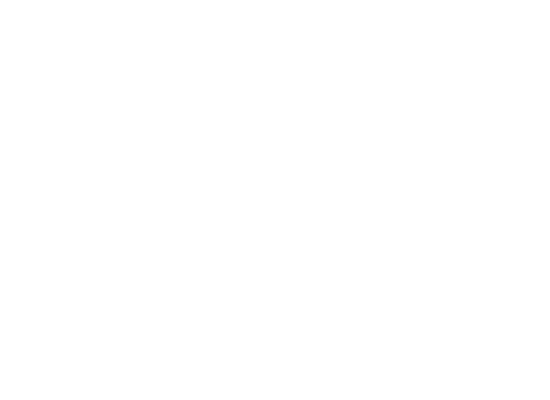Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum. (Wisuda IKJ 2006)
endidikan Kesenian dalam Kebudayaan Urban
Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum.
Pidato Ilmiah dalam Wisuda Institut Kesenian Jakarta Tahun 2006
Tuan-tuan dan Puan-puan yang Terhormat,
Telah menjadi pengetahuan bersama, bahwa pendidikan kesenian sebetulnya bisa berlangsung di mana saja.
Dalam masyarakat yang tersepakati sebagai komunitas tradisional, pendidikan kesenian diberlangsungkan tanpa memberi beban kepada para pembelajarnya dengan tujuan dan cita-cita dari sikap berkesenian masyarakat yang terumuskan sebagai modern, seperti menjadi “seniman professional”. Telah diketahui bersama, kesenian dalam kehidupan masyarakat seperti ini adalah bagian saja dari ritus tradisi itu sendiri, tempat setiap lapisan sosial mendapat peranannya masing-masing, dan pengertian “seniman” sebagai bidang profesi yang eksklusif tidak dikenal meski kemampuan berkeseniannya barangkali setara dengan kemampuan seorang maestro.
Sementara itu, dalam masyarakat yang terarahkan sebagai bagian dari cita-cita modernitas, pendidikan kesenian tetap juga bisa berlangsung di mana saja sering dikisahkan anekdot faktual, betapa seorang Steven Spielberg gagal masuk ke sekolah tinggi film, tetapi dengan cara magang akhirnya berhasil menjadi seorang sutradara film-film yang menjadi tolok ukur teknologi film mutakhir, yang produktivitasnya sulit diimbangi para lulusan sekolah film manapun di dunia, termasuk di negerinya sendiri.
Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang Saya Hormati,
Pengantar ini bukan mau menunjukkan bahwa institusi pendidikan kesenian yang formal tidak terlalu berguna, melainkan bermaksud membuktikan bahwa secara formal maupun tidak formal, suatu pembelajaran untuk mencapai taraf berkesenian yang optimal ternyata merupakan sesuatu yang mutlak—karena kesenian yang hanya bermodalkan “ilham” adalah suatu takhayul. Sebaris puisi yang paling pendek sekalipun, tidak mungkin menjadi berharga tanpa kerja keras pengenalan dan pengolahan bahasa, yang mustahil menjadi suatu pengetahuan dengan seketika. Kualitas dicapai melalui suatu proses, bukan oleh kebetulan.
Perbedaan antara belajar kesenian secara formal dan tidak formal, yang mudah terkelirukan dalam kelembagaan dan ketidakterlembagaannya, adalah bahwa yang formal ini terandai-andai memberlangsungkan proses belajar secara sistematis. Tempat proses itu tidak dimaksudkan berlangsung secara alamiah, melainkan secara terarah dan tertata berdasarkan tujuan, kebutuhan, maupun kepentingan tertentu. Dengan kata sistematis, artinya berlangsung pendekatan belajar-mengajar dalam kerangka terdapatnya ukuran-ukuran, kriteria, kategorisasi, dan klasifikasi yang mesti terpilah secara jernih. Dengan kalimat yang lebih populer, pendekatan institusi pendidikan kesenian yang sistematis ini adalah pendekatan yang mengandaikan terdapatnya suatu standar dalam kesenian—bagaikan bisa menentukan termungkinkannya suatu standar dalam keindahan. Padahal, pada billboard yang terpasang di depan Taman Ismail Marzuki, tertulis dengan huruf-huruf besar: Standar sudah tidak ada lagi.
Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang Amat Saya Muliakan,
Dilema sebuah lembaga pendidikan kesenian seperti IKJ, bukanlah sekadar bahwa pedoman-pedoman dalam dunia seni yang selama ini dianggap sebagai kebenaran-tak-terpertanyakan telah menjadi babak belur bahkan hancur, melainkan bahwa keberadaannya di tengah sebuah kota seperti Jakarta memang membuatnya terbuka sebagai situs pergulatan berbagai macam gagasan. Apa boleh buat, IKJ adalah lembaga pendidikan kesenian yang tumbuh dan berkembang di tengah kebudayaan urban, tempat tradisi telah menjadi keropos tetapi modernitas terlalu sering hadir sebagai proyek kesempurnaan yang gagal. Maka dalam apa yang disebut kebudayaan urban, segala aspirasi kesenian, yang klasik maupun yang populer, yang elitis maupun yang kampungan, yang “borju” maupun yang proletar, yang konservatif maupun yang kontemporer, yang komersial maupun antikomersial, berjuang merebut tempatnya dalam suatu pergulatan antarwacana yang boleh diyakini berlangsung setiap saat dan kemungkinan besar tidak akan pernah ada habisnya.
 Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)
Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)
Dengan pemahaman bahwa wacana dominan akan selalu mendapat perlawanan dari kelompok terbawahkan, berita semacam ini sebenarnyalah tidak terlalu mengejutkan telah umum diketahui, hegemoni wacana dominan hanya tetap bisa bertahan jika bernegosiasi dengan wacana perlawanan tersebut.
Dengan demikian, dalam berbagai bentuk dan sikap berkesenian di sebuah atmosfir kebudayaan seperti Jakarta, standar yang pernah diandaikan berlaku umum (universal) dan selama-lamanya (abadi) sudah tidak dapat dipertahankan, bukan saja karena standar oposisional “seni tinggi” dan “seni rendah” telah lenyap menguap dalam cara pandang yang mau tidak mau harus diperbarui, tetapi juga karena yang dianggap beroposisi telah saling bernegosiasi dalam inkorporasi. Bukankah industri kesenian yang bersifat massal telah mengubah struktur sosial dan politik dalam seni, yang semula sangat kokoh membedakan seni adiluhung dan seni kodian, menjadi sangat relatif? Ketika kecanggihan teknologi membuat reproduksi karya seni bukan saja lebih indah, melainkan juga lebih murah, dari karya aslinya; bukankah pandangan romantik tentang otentisitas karya seni yang agung dan otoritatif tidak saja memudar seperti kabut pagi, melainkan juga telah berlangsung demokratisasi pandangan dalam penilaian sebuah karya seni? Keindahan seni ternyata bukanlah suatu esensi, melainkan konstruksi suatu tradisi sosial historis, yang terus berproses ketika faktor-faktor pendukungnya berganti dan berubah.
Ini berarti sebuah institusi pendidikan kesenian di Jakarta seperti IKJ, yang telah menerapkan standar tertentu dalam menerima dan meluluskan mahasiswa, bahkan para dosen mengajarkan dan menguji penguasaan suatu standar keilmuan dalam kesenimanan maupun kesarjanaan, tertuntut untuk bersikap bukan hanya lebih terbuka, tetapi lebih jauh lagi justru merengkuh segenap kemungkinan perkembangan yang telah diperlihatkan gejala-gejala tersebut. Menutup diri dalam tempurung kesenian yang eksklusif, hanya akan membuat IKJ dan lulusannya terasing dari proses sosial yang berlangsung di luar tembok kampusnya karena dalam kebudayaan urban, tempat IKJ secara eksistensial menjadi bagiannya, berlangsung pula sebuah ekonomi budaya.
Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang Mulia lagi Budiman,
Izinkanlah saya menyampaikan bahwa ekonomi budaya tidak berproses secara sama dan sebangun dengan perhitungan yang berlangsung dalam ekonomi finansial, karena jika ekonomi finansial menyelesaikan persoalannya dengan angka-angka untung dan rugi, maka dalam ekonomi budaya jual-beli berlangsung secara lebih kompleks. Ekonomi budaya memberi peran besar justru bukan kepada seniman sebagai produsen karya seni, melainkan kepada konsumen yang terbebaskan dari berbagai tetek bengek standar kesenian, untuk memberikan penghargaan kepada karya seni apapun yang muncul di hadapannya bukan berdasarkan pemahaman atas suatu standar estetika tertentu, melainkan dari faktor kenikmatan, makna, dan identitas sosial yang akan didapatkannya secara subjektif. Sumber makna karya seni lepas dari tangan seniman dan kritisi, direbut oleh tangan-tangan konsumen yang harus dianggap sebagai tindakan produktif dalam menanggapi sebuah karya seni untuk menjadi berguna dalam hidupnya sehari-hari.
Kebudayaan urban dibentuk oleh masyarakat yang heterogen, masyarakat yang setiap individunya merupakan subjek dengan pluralitas teks dalam dirinyapun heterogenitasnya telah dan masih akan diacak-acak oleh setidaknya lima ranah yang saling bersilang dalam arus lalu lintas global di atas bola bumi. Itulah ranah etnik, ranah ideologi, ranah finansial, ranah media, dan ranah teknologi. Kesalingbersilangan lima ranah yang dalam berbagai varian perjumpaannya membentuk berbagai momentum, berjuta-juta momentum, bermilyar-milyar momentum sosial historis dalam kehidupan sehari-hari kita. Kelima ranah tersebut telah menjadi faktor-faktor menentukan dalam suatu relasi kuasa yang membentuk wacana kita bersama tak terkecuali menerobos masuk tembok-tembok kampus IKJ. Penting untuk dicatat, kelima ranah pembentuk arus budaya global ini tidak akan pernah berhasil menyeragamkan manusia, sebaliknya justru membuat setiap orang mampu membentuk dan memperkaya identitas budayanya sendiri.
Maka, masihkah konstruksi pemahaman berkesenian dalam institusi pendidikan formal bertahan, untuk selalu teracu kepada suatu standar estetika tertentu? Masihkah para pengajar maupun mahasiswanya akan bersikap membutababi, tenggelam dalam mahligai keindahan seni untuk diri dan komunitas eksklusifnya sendiri, seolah-olah di luar kampusnya tidak pernah berlangsung tsunami, gempa bumi, Munir terbunuh, bayi-bayi terkapar mati karena kurang gizi, dan berlangsung hiruk pikuk pro dan kontra rencana undang-undang antipornografi? Para pengamen hampir selalu melagukan protes sosial di dalam bis kota, suatu penanda bahwa konstruksi sosial politik menjadi wahana pembelajaran bagi mereka yang tidak beruntung mengalami pendidikan kesenian secara formal—mestikah, dengan begitu, lembaga pendidikan formal membuang peluang dari segenap kemungkinan dalam kebudayaan urban, untuk menjadikannya wacana dalam perbendaharaan akademik, demi kepentingan mutu kesenimanan dan kesarjanaan para lulusannya?
Dunia sudah berubah. Harus atau tak haruskah IKJ berubah?